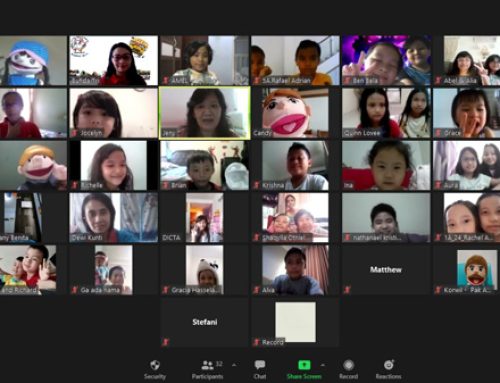Sebuah gelas aqua bekas tergantung di teras rumah. Pada hari-hari tertentu, bapak mengisi gelas aqua tersebut dengan uang perak pecahan lima ratus atau segenggam beras. Pagi harinya, gelas aqua tersebut kembali kosong. Petugas ronda di kampunglah yang mengumpulkan isi gelas aqua tersebut dari rumah ke rumah. Itulah kenangan masa kecil saya, sekitar akhir tahun 1990 di sebuah kampung kecil di Jogja.
Jimpitan beras, sebuah tradisi yang mungkin sebagian dari kita bahkan belum pernah mendengarnya. Konon tradisi ini berasal dari Jawa terutama di daerah pedesaan, dimana secara rutin, masyarakat mengumpulkan beras sejimpit untuk disimpan sebagai cadangan. Hal tersebut dilakuka sebagai sebuah langkah antisipasi apabila musim paceklik tiba. Jadi apabila sebuah keluarga mengalami gagal panen, keluarga tersebut bisa meminjam dahulu beras hasil jimpitan tersebut, sehingga mereka pun tidak mengalami kelaparan. Beberapa nilai yang ingin dikembangkan dalam tradisi ini diataranya: kebersamaan (gotong royong), keterbukaan (transparansi), kemandirian (swadaya) dan belas kasih (persaudaraan). Dalam perkembangannya, materi berupa beras tersebut bisa digantikan dengan uang logam, dengan pertimbangan kepraktisan dan atau alasan lainnya.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jimpitan mengandung arti: 1. hasil menjimpit; jumputan; 2. sumbangan berupa beras sejimpit yang dikumpulkan secara beramai-ramai. Sedangkan kata dasar jimpit sendiri berarti mengambil dengan ujung telunjuk dan ibu jari.
Pertanyaan yang kemudian muncul: Apakah di kota besar seperti Jakarta ini, tradisi tersebut masih bisa kita jumpai? Apakah tradisi tersebut masih relevan di jaman modern ini?
Adalah sebuah lingkungan di Gereja Santo Gabriel Paroki Pulo Gebang, Lingkungan Santo Fransiskus Asisi, bagian dari Wilayah I, yang masih nguri-uri tradisi jimpitan beras tersebut dan mengimplementasikan menjadi program rutin di lingkungan Fransiskus Asisi. Dalam keterangannya, bapak Albertus Aldi Noviandiko Haryono (biasa dipanggil mas Aldi), ketua Lingkungan Santo Fransiskus Asisi, menyampaikan: “Program jimpitan beras ini merupakan gagasan dari ketua lingkungan pada periode sebelumnya (bapak F. Maryanto), dan sudah berlangsung selama 8 tahun. Tujuan utama dari program ini adalah menumbuhkan solidaritas umat di Lingkungan Asisi untuk mau membantu, bukan dalam bentuk uang tetapi berupa kebutuhan pokok (beras)”. Dalam prakteknya, beras yang berasal dari umat lingkungan dikumpulkan ke Seksi Sosial Lingkungan, untuk kemudian dikelola dan dibagian kepada umat lingkungan yang membutuhkan. “Dari 29 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Lingkungan Asisi, ada 5 KK menerima bantuan beras ini, sementara ada 10 KK yang berpartisipasi tetap menjadi penyumbang, sedangkan KK yang lain tentatif”, demikian mas Aldi melanjutkan penjelasannya.
Di tengah budaya individualisme yang kian menjamur, tradisi yang kita temui di Lingkungan Santo Fransiskus Asisi ini, bagaikan air yang menyejukkan dahaga. Satu hal yang tidak kalah menarik adalah bagaimana bantuan beras tersebut dikumpulkan. Seperti dijelaskan oleh mas Aldi, pada awal-awal program jimpitan beras, SSL yang aktif mendatangi rumah pada donatur untuk mengumpulkan beras. Akan tetapi sekarang ini, setiap donatur dengan inisiatif sendiri mengumpulkan beras sumbangan ke SSL atau membawanya pada saat pertemuan lingkungan. Apakah ini implementasi nyata dari apa yang bisa kita baca dalam Kis. 4:34-35?
Sebuah khayalan pun melintas. Jika ada 1,000 KK di Paroki Pulo Gebang yang setiap bulannya bisa berbagi 1kg beras saja, maka akan ada 1 ton beras yang bisa dibagi kepada umat Paroki Pulo Gebang dan warga sekitar gereja yang membutuhkan. Tidak perlu menunggu event Natal, Paskah atau Lebaran, kita akan bisa berbagi dengan umat kita yang “kurang beruntung”. Bukankah itu salah satu implementasi nyata dari “Makin Adil, Makin Beradab”, tema besar yang kita usung di tahun 2017 ini. (masdi2t)